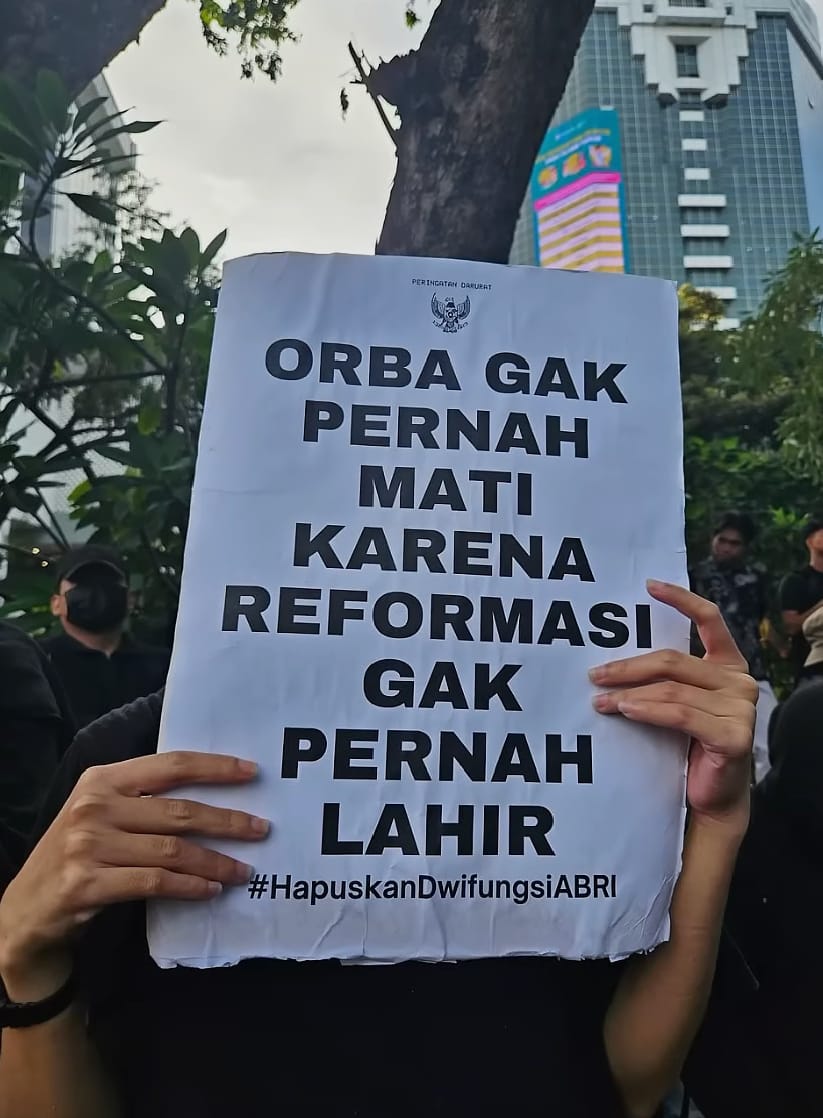Kepemimpinan sering kali di maknai sebagai ranah sorang laki-laki, praktek dalam masyarakat masih banyak yang berpandangan patriarki, seringkali untuk menempati posisi dalam tataran petinggi adalah laki-laki, sebagai contoh dalam masyarakat desa ketua RT, RW dan kepala desa mereka lebih mempercayakan amanat tersebut kepada seorang laki-laki, perempuan di rekonstruksi arah geraknya dalam masyarakat hanya sebatas penguasa peran domestik saja, mereka kurang mendapat ruang gerak yang bebas untuk ikut andil dalam membuat kebijakan publik.
Pandangan tersebut adalah sebuah pandangan gender sebagai sebuah sistem sosial, dimana peran dan atribut gender itu di pelihara dengan sengaja dan dilanggengkan dalam unit-unit sosial yang terangkum menjadi sistematis kemudian dijalankan secara rapi, karena praktek ini berlangsung dari masa ke masa, terekonstruksi dengan sengaja karena budaya yang membangun bahwa perempuan lebih besar karakter feminimnya dari pada maskulinitasnya, kemudian pandangan yang sudah ada di masyarakat terkait minoritas perempuan itu terpelihara dan di benarkan serta di lestarikan hingga jadilah stereotype yang menjadikan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang lebih super dari pada perempuan.
Sejatinya peran perempuan di Indonesia memiliki posisi yang ambigu dalam masyarakat. Di satu sisi, perempuan di minta untuk selalau tampil sebagai manusia yang baik-baik, welas asih, bijak, pandai mengelola keluarga dan cerdas mendidik anak. Bahkan, mayoritas tanggung jawab membina keluarga di serahkan kepada perempuan. Akan tetapi, sedari kecil mayoritas perempuan Indonesia tidak memiliki akses untuk membentuk kapasitasnya. Itulah mengapa peran perempuan untuk dapat menjadi lakon dalam tataran kepemimpinan merupakan hal yang riskan untuk di capai.
Jika kita flash back ke era zaman kerajaan bangsa Indonesia, Kedudukan perempuan di Indonesia tempo dulu memiliki pengaruh yang besar. Perempuan mempunyai tempat yang sangat baik, mendapat penghargaan dan derajat yang sama dengan laki-laki. Hampir di seluruh daerah di Indonesia pernah mengalami pengaruh besar dari penguasa perempuan dalam pemerintah. Beberapa peristiwa dimana perempuan menjalankan pengaruh yang menentukan dalam pemerintah dan menentukan kebijkan publik, secara terbuka maupun terselubung. Beberapa contoh kepemimpinan perempuan di nusantara, Ratu Sima dari Kerajaan Keling, Tri Bhuwana Tungga dewi dari bangsa Isyana dan Ratu Kalinyamat dalam sejaran Demak, menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional Indonesia tidak menolak penguasa perempuan.
Bagaimanakah peran perempuan dalam ranah pemerintahan masa kini?
Dalam sebuah kajian Lembaga penelitian Semeru menjelaskan bahwasannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan visi “Otonomi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat” memberikan harapan terbukanya peluang lebih luas bagi peran masyarakat laki-laki maupun perempuan secara lebih aktif. Tidak lama setelah keluarnya undang-undang tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid (Presiden RI pada waktu itu) mengeluarkan Inpres No. 9/2000 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender. Salah satu dampak penting kebijakan ini adalah aksi afirmatif dalam UU Pemilu No. 12/2003 yang mewajibkan kuota 30% calon perempuan dalam pengajuan daftar calon legislatif (caleg) partai politik pada saat pemilihan umum. Kebijakan ini merupakan salah satu indikator perubahan sikap politis pemerintah mengenai masalah gender. Dalam sejarah perkembangan pemilu legislatif di Indonesia, prosentase tertinggi keterwakilan perempuan pernah dicapai pada Pemilu DPR 1987, yaitu 13% dari total 565 anggota DPR. Memasuki era reformasi, ternyata keterwakilan perempuan di DPR belum mengalami perubahan signifikan. Pada Pemilu 1999, misalnya, keterwakilan perempuan hanya 9% dari 546 total anggota DPR. Setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan, meski mengalami sedikit peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2004 masih lebih rendah dari Pemilu DPR Tahun 1997 karena hanya meraih 11,3% dari 550 anggota DPR periode tersebut (CETRO, 2).
Pemilu legislatif 2009 juga memperlihatkan situasi mirip seperti yang terjadi dengan kontes pilkada saat ini. Jumlah caleg perempuan DPR adalah 34,7% ( atau 3.895 orang dari total 11.218 caleg) sedangkan yang terpilih 18% (101 perempuan dari total 560 anngota DPR RI). Untuk caleg DPD, total jumlah caleg perempuan tercatat 11,2% ( 1.113 perempuan) dan caleg yang terpilih mencapai 27,7% (36 perempuan dari 132 perempuan).
Secara keseluruhan peran perempuan dalam politik cukup menunjukan peningkatan yang cukup signifikan dari tataran lokal maupun nasional, namun pertanyaannya adalah siapakah perempuan-perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen saat ini? Fakta menunjukan bahwa sebagian besar anggota legislatif baru ditingkat nasional berasal dari dinasti politik, figur popular ( dengan jaringan banyak dan kemampuan finansial yang kuat), serta sedikit kader partai yang berjuang dari bawah. Justru kalangan aktivis, yang telah lebih banyak pengetahuan dan pengalaman bersentuhan dengan isu gender serta pemberdayaan kelompok marjinal, amat sedikt jumlahnya.
Maka tak heran jika para penguasa kursi kepemimpinan yang di di duduki oleh perempuan, menuai problem terkait masalah korupsi, karena alsannya para perempuan yang terpilih kebanyakan dari kaum elit politik dan sedikit dari kalangan yang benar-benar ingin membawa kemajuan terhadap masyarakat.
Sejak reformasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan representasi politik perempuan, misalnya dengan penerapan kuota 30% caleg perempuan serta pemberlakuan “zipper system” untuk daftar kandidat pemilihan legislatif 2009. Dengan “zipper system” ini, parpol harus memasukan paling tidak satu perempuan dari tiga kandidat agar peluang terpilihnya menjadi lebih besar. Sayangnya, efektivitas ketentuan-ketentuan ini jauh berkurang sesudah Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu Indonesia dari representasi proporsional menjadi sepenuhnya terbuka.
Hingga saat ini masih banyak dipertanyakan apakah jumlah keterwakilan perempuan dapat secara efektif menjamin agar kebutuhan dan kepentingan perempuan dapat disuarakan. Walaupun sebenarnya tidak ada jaminan ke arah itu, tetapi aksi afirmatif selama ini memang dijadikan alat sebagai sebuah tindakan proaktif untuk mengurangi kesenjangan jumlah dan akses perempuan di tingkat pengambil kebijakan dalam masalah politik dan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak perempuan yang duduk dalam posisi pengambilan kebijakan, maka semakin besar peluang untuk memasukkan kepentingan perempuan ke dalam agenda nasional.
Dengan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa peningkatan representasi perempuan berkorelasi dengan banyak faktor baik politik maupun non-politis. Telah kita lihat bahwa regulasi dan institusi politik –walaupun penting- ternyata belum bekerja optimal dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (politics of ideas and presence). Kondisi pembangunan manusia Indonesia adalah basis yang amat signifikan memengaruhi bagaimana kesetaraan dan keadilan gender di arena politik bisa di capai.
Keadilan gender di arena politik membutuhkan persyaratan pemenuhan kebutuhan dasar individu ( laki-laki dan perempuan) berupa pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang baik untuk bisa mengakses peluang atas sumber daya ekonomi maupun politik. Aspek perlindungan (yang digagas lewat kebijkan afirmatif untuk perempuan di arena politik bertujuan untuk menutup gender gap ini). Gagasan afirmatif dirancang untuk memberi peluang “kemudahan bagi kaum perempuan “ untuk bisa di arena pengambilan kebijakan. Harapannya, kualitas kebijakan yang dihasilkan akan menolong teman-teman mereka yang renta, kelompok marjial dan individu yang tersisih dalam proses, dan terkena dampak kebijakan yang selama ini bias gender atau netral gender yang memingirkan kelompok tersebut. Setiap warga Negara seharusnya berhak menikmati hak dasar dan bisa ikut mengakses peluang ekonomi dan politik yang sebetulnya melekat pada mereka.
Di wilayah dengan kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, maka faktor social budaya, adat istiadat, penfsiran agama, dan redahnya pemahaman pemimpin local membuat tantangan perempuan untuk berpartisipasi di arena politik menjadi berlipat kali lebih berat dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah menikmati indeks pembangunan gender yang lebih baik.
Daerah dengan kebutuhan dasar yang relatif terpenuhi, dan dengan kesenjanan gender yang tidak terlalu timpang, biasanya paralel dengan keterwakilan perempuan yang lebih baik. Kendala cultural hampir tidak lagi signifikan memengaruhi partisipasi perempuan di arena politik. Logika politik dimakanai secara personal sebagai kontestasi ekonomi dan kekuasaan, untuk pemenuhan kebutuhan power dan uang yang sangat individualistic. Sementara untuk kelompok miskin,, arena politik di gunakan sebagai medan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sedangkan perempuan terpilih tidak sepenuhya independen dari pengaruh politisasi etnis, kasta dan kedaerahan, dan agama yang lekat di wilayah-wilayah yang secara social-ekonomi masih memprihatinkan. Mereka cenderung menjadi kepanjangan tangan dari penguatan dari penguatan nilai-nilai patriarki dan nilai maskulin dalam politik.
Bagaimana perempuan atau kartini masa kini, apakah politik sebagai ancaman atau sebaliknya poitik sebagai peluang?
Oleh : Siti Nur Maela