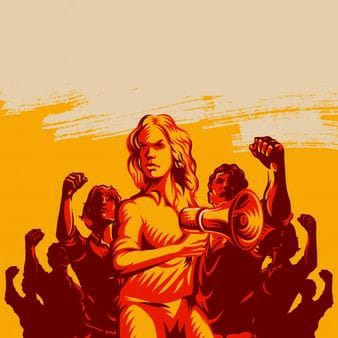Judul: Saman
Penulis: Ayu Utami
Tahun Terbit: 1998
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
ISBN: 978-979-91-0570-7
“Bagiku hidup adalah menari, dan menari pertama-tama adalah tubuh […] Tubuhku menari. Sebab menari adalah eksplorasi yang tak habis-habis dengan kulit dan tulang-tulangku, yang dengannya aku rasakan perih, ngilu, gigil, juga nyaman. Dan kelak ajal.” (Shakuntala~ dalam Saman karya Ayu Utami)
Sejarah telah menyebutkan bahwa pengalaman kehidupan yang ditempuh manusia (sebenarnya) adalah tentang pengalaman kebertubuhan. Tubuh semata-mata hadir dan dijadikan dasar untuk melihat sekaligus membuat penilaian terhadap eksistensi manusia. Tak hanya itu, bahkan tubuh menjadi sentral kebebasan (juga kebahagiaan) dikonstruksikan. Nilai, norma, hukum, moralitas, (bahkan agama) hadir secara sibuk untuk mengurus secara ketat keberadaan tubuh manusia.
Singkat dan jelasnya, secara melompat ingin saya katakan, kebebasan dan kebahagiaan manusia adalah barang yang sukar dan mahal, karena kebebasan dan kebahagiaan terkait penuh dengan tubuh, sedangkan tubuh diurus (diatur) secara ketat oleh nilai, norma, hukum, moralitas juga agama. Manusia sebagai diri (sesungguhnya) tak benar-benar memiliki tubuhnya. Tubuh, sebagai dan secara being, tak pernah dirasakan kehadirannya dengan pure dalam ruang kesadaran manusia. Nilai-nilai yang secara sibuk mengurus (mengatur) tubuh itulah yang dimiliki dan dirasakan dalam ruang kesadaran hidup manusia.
Modernitas yang kemudian hadir—dengan mendeklarasikan dirinya seolah sebagai pihak yang telah mencapai peradaban wahid—secara arogan dan “kriminal” membentuk suatu wacana (dalam bentuk nilai-nilai, norma, hukum, moralitas) untuk kemudian secara “brutal” ia jadikan piranti guna mengatur kehidupan manusia—dalam konteks ini adalah, tubuh. Karena di situlah eksistensi manusia bersemayam. Dalam konteks inilah, wacana modern Barat terhadap ‘kebertubuhan’ harus dipahami sebagai bentuk kolonialisasi, penjajahan. Sebab, segala pengaturan itu analog dengan ciri penjajahan. Tak hanya itu, bahkan dengan sedemikian rupanya tubuh oleh masyarakat modern diberikan nilai, diatur, dan akhirnya dipromosikan pula sebagai komoditi. Proyek modernitas yang dipusatkan pada tubuh adalah cara bagaimana hegemoni modern hendak memenuhi segala kebutuhan kapitalnya.
Meski tubuh adalah milik laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam runtutan sejarahnya terkait dengan bentuk-bentuk (wacana) aturan terhadap tubuh. Dalam konteks tertentu, pihak perempuanlah yang pada akhirnya paling mengalami derita ketidakadilan. Seksualitas, dalam arti sebagai sesuatu yang telah “diwacanakan”, telah membawa keberadaan tubuh perempuan sebagai sesuatu yang bukan miliknya (baca: milik perempuan). Tubuh perempuan justru dimiliki oleh segala hal yang berada di luar diri perempuan. Yakni, milik norma kebudayaan (patriarki), milik komoditi pasar (iklan), milik wacana kuasa (politik), dan milik agama dan hukum adat (perkawinan). Karena pada prinsipnya, dorongan seksual (fisik) dapat dipuaskan, atau lebih tepatnya adalah milik si pemilik tubuh dengan semua cara aktivitas tubuhnya. Maka, ketika wacana seksualitas pada tubuh kemudian diatur-atur, tentu hal demikian akan berubah menjadi bentuk praktik ketidakadilan.
Perempuan menjadi subordinat dalam banyak sektor. Ia mengalami diskriminasi pula dalam berbagai hal. Tubuh perempuan dikooptasi dengan sedemikian rupa, sehingga perempuan menjadi kehilangan kendali etis atas tubuhnya menjadi suatu praktik yang mestinya tidak terus-menerus dilanggengkan. Determinasi tubuh perempuan yang dilakukan oleh wacana atau nilai-nilai aus tidak bermutu itu pulalah yang coba didekonstruksikan oleh Ayu Utami dalam novelnya, Saman.
Satu hal penting yang harus dilihat dan dipahami, bahwa Ayu Utami membawakan ide dan ceritanya dalam karya tersebut, tidak semata-mata hanya menuliskan kegeramannya akibat adanya iri terhadap kaum laki-laki. Ayu Utami justru membawa ide dan menjalankan cerita dalam novel yang terbit di zaman sebelum reformasi tersebut dengan melandaskannya pada pengalaman orisinil seorang perempuan. Sebagaimana yang disebutkan Sagita Putri dalam tulisannya, Ayu Utami dalam menuliskan karyanya ini mengacu pada tokoh Virginia Woolf (1882) yang memberikan dasar bahwa penulis perempuan adalah penulis yang lebih berpretensi mengeksplorasi “pengalaman” perempuan, bukan hanya sebatas membandingkan dirinya dengan peran laki-laki dalam kancah kehidupan masyarakat.
Betapa menariknya Ayu Utami membawakan empat tokoh perempuan dalam novelnya tersebut untuk menjadi representasi penentangan terhadap nilai (wacana) perempuan yang sudah lama menjadi belenggu. Khususnya belenggu terhadap tubuh perempuan. Peranan sekaligus karakter yang digambarkan dalam sosok Yasmin, Laila, Shakuntala, dan Cok adalah bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan perempuan atas belenggu-belenggu wacana patriarki, termasuk juga kelas sosial. Penentangan terhadap norma patriarkis, misalnya dalam urusan perkawinan, pekerjaan, dan pendidikan, secara jelas dapat dilihat tentang bagaimana Shakuntala yang begitu “membenci” bapaknya, karena menurutnya, merupakan simbol dari sistem pratiarki itu sendiri dan yang berkepentingan untuk selalu melanggengkannya.
Belenggu patriarki pada akhirnya berdampak pada bagaimana seksualitas perempuan sebagai ruang ekspresi kebutuhan terhadap seks dikonstruksikan dalam habitus (baca: kebudayaan) masyarakat. Perempuan seolah-olah hanyalah pelengkap gairah seksualitas laki-laki yang menjadikan perkawinan sebagai arena untuk memberlangsungkan praktik dominasi seksualitas laki-laki terhadap perempuan. Perkawinan bermakna sama dengan penundukan. Dominasi itulah yang menjadikan perempuan subordinat sebagai makhluk yang sesungguhnya juga sama-sama diberikan hasrat seksual dalam hidupnya.
“… dua pelajaran pertamaku tentang cinta […] Pertama. Hanya lelaki yang boleh menghampiri perempuan. Perempuan yang mengejar-ngejar lelaki pastilah sundal. Kedua. Perempuan akan memberikan tubuhnya pada lelaki yang pantas, dan lelaki itu akan menghidupinya dengan hartanya. Itu dinamakan perkawinan. Kelak, ketika dewasa, aku menganggapnya persundalan yang hipokrit.” (Shakuntala, “Saman” Ayu Utami, h. 123)
Betapa posisi perempuan, termasuk terhadap eksistensi tubuhnya, yang dikooptasi sedemikian rupa tersebut seolah-olah adalah semata-mata milik lelaki. Sehingga mengakibatkan perempuan tak bisa leluasa merasakan kehadiran diri(tubuh)nya dalam artian yang sesungguhnya. Perempuan terpenjara di dalam belenggu nilai (wacana) yang mendiskreditkan obsesinya sebagai juga seorang makhluk. Apalagi tatkala hasrat seksualitasnya hanya boleh dipahaminya sebagai bentuk “ketundukan” terhadap lelaki.
Padahal, dalam kebudayaan luhur Jawa, seks tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang tabu, yang harus diprivatisasi sedemikian rupa. Dalam Sastra Jendra, seks justru dipahami secara luhur sebagai aktivitas mencari rahasia alam (wewadining jagad). Representasi seksual yang notabene merupakan bentuk anugerah Tuhan sebagai makhluk yang berhasrat mestinya tidak dibatasi dalam artian sebagai sesuatu yang represif nilai bagi kaum perempuan. Tubuh (milik perempuan) juga memiliki hak dan kebebasan untuk mengekspresikan kebutuhan seksualnya. Tatkala wilayah ini dikonstruksikan dalam ruang yang tabu, yang perempuan harus bersikap tertutup dan tunduk, maka ini menjadi praktik ketidakadilan yang berselubung.
Pada konteks demikian pulalah, Ayu Utami lewat novel Saman-nya, ingin memberikan penentangan nilai—apabila tidak boleh disebut pembalikan nilai—terhadap kehadiran norma, moralitas, bahkan agama terkait kebutuhan seksualitas. Agama misalnya, tak seharusnya diperalat untuk membelenggu perempuan akan kebutuhan seksualitasnya yang mesti tunduk di bawah ”libido” kepentingan lelaki. Di mana menurut ajaran agama, dosa dan seorang istri yang sarat beban adalah perempuan yang seluruh tubuh dan kemampuan reproduksinya mutlak merupakan milik eksklusif suami. Sehingga ia (perempuan) mesti tunduk terhadap si lelaki. Bahkan, kutukan dilegal-formalkan sebagai bentuk hukuman apabila ia (istri) melanggar aturan hubungan antar suami dan istri. Apakah agama sungguh-sungguh hanya hadir memberikan wacana yang sungguh nian patriarkinya?
Saya ingin menegaskan kembali, segala sesuatu sifatnya penuh kepentingan yang berat sebelah, adalah sesuatu yang mesti dibongkar, juga dilawan. Meminjam kacamata analisa Foucault misalnya, mengenai dominasi atau kuasa, mengatakan bahwa kombinasi kekuatan eksternal dan pengaturan dan pengawasan internal terhadap diri (dalam konteks ini, adalah tubuh perempuan) menjadikan wacana kekuasaan (patriarki) sukar terbendung. Bukan hanya sebatas itu, bahkan keberadan tubuh, disadari atau tidak, telah dikodifikasi demi kepentingan-kepentingan tertentu.
Sebagai contoh, istilah “fetisisme tubuh” muncul akhirnya sebagai suatu agenda politis-materialis-ekonomis yang dilakukan oleh kaum berkuasa lewat wacana-wacana (norma) yang diciptakannya. Dilihat ketajaman analisa kuasa Foucault lagi, bahwa bentuk-bentuk wacana (norma-norma kebudayaan) tidak lain adalah digunakan untuk meregulasi, mengendalikan, dan mendisiplinkan sesuatu yang ingin dikuasainya. Ini pulalah yang terjadi pada eksistensi kebertubuhan perempuan. Sehingga novel Saman, sebagai novel feminis ini, hemat saya merupakan upaya penentangan, termasuk penyadaran atas bentuk-bentuk konstruksi pikiran ketidakadilan atas perempuan.
Terlepas dari kevulgaran bahasa (kata) yang digunakan oleh Ayu Utami dalam novelnya tersebut. Pada intinya, segala bentuk-bentuk pemikiran yang membikin kesadaran perempuan berada dalam bilik inferioritas atas lelaki menjadi suatu yang mesti ditentang dan dibongkar. Perempuan dengan tubuhnya adalah kombinasi kebebasan (kebahagiaan) yang tidak semestinya dibatasi oleh pandangan-pandangan yang tabu dan subordinat.
Perempuan sudah semestinya memiliki kebebasan atas tubuh miliknya sendiri. Karena di situlah kehadiran perempuan dapat dirasakan dan dinikmati, utamanya oleh diri perempuannya sendiri. Persis seperti yang Ayu Utami gambarkan dengan sosok Shakuntala sebagai seorang penari, yang saya kutipkan berikut: “Bagiku hidup adalah menari, dan menari pertama-tama adalah tubuh.” Lanjutnya, “Tubuhku menari. Sebab menari adalah eksplorasi yang tak habis-habis dengan kulit dan tulang-tulangku, yang dengannya aku rasakan perih, ngilu, gigil, juga nyaman. Dan kelak ajal.” (Ayu Utami, Saman, h. 118)
Penulis: Ahmad