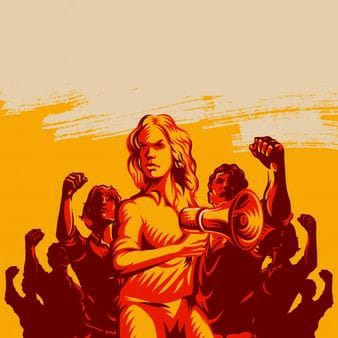Pintu depan utama pasar Gede dengan arsitektur yang bisa terbilang unik.
“SAYA TIDAK BERGAMA KATOLIK.”
Sumantri Dana Waluya masih duduk di bangku sekolah kelas tiga sekolah menengah atas di salah satu sekolah swasta di Solo pada tahun 1975 lalu. Bukannya menjawab soal ujian akhir mata pelajaran agama Katolik yang harusnya ia selesaikan saat itu, ia menulis kalimat lain secara kapital di tengah-tengah lembar jawaban.
“Sekolah saya 99%-nya adalah Tionghoa, tapi kami diminta memilih Kristen atau Katolik. Saya tulis seperti itu saja untuk protes. Eh kami semua dapat nilai 7 pukul rata,” kenangnya yang kini menjabat sebagai Ketua Yayasan Klenteng Tien Kok Sie, yang biasa disebut juga Klenteng Pasar Gede.
Apa yang dilakukan Sumantri kecil mungkin terdengar biasa saja. Namun, Sumantri yang sedari kanak-kanak mengalami ragam diskriminasi dikarenakan agama yang diyakininya, percaya bahwa saat itu apa yang dilakukannya adalah bentuk ketidaksepakatannya terhadap pemaksaan pada dirinya.
Walaupun sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Konghucu baru mendapat pengakuan dari Negara pada 2000 silam saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Ya saya senang, merasa hak-hak sipil saya sudah mulai dikembalikan. Karena awalnya saya enggak peduli mau ditulis agama apa, karena keyakinan saya ada di hati bukan di KTP,” ungkap Sumantri.
Sambil bertutur pelan, Sumantri berkisah cerita hidupnya sebagai seorang Konghucu keturunan Tionghoa di Indonesia, terutama dengan keberadaan kelenteng yang dikelolanya berada di tengah-tengah Pasar Gede.

Dilansir dari sejuk.org dalam tulisan Geger Pacinan, Angkat Sejarah Sekutu Tionghoa-Jawa yang Terlupakan, peristiwa nahas yang terjadi pada rentang tahun 1740-1743 itu berawal dari pembantaian masyarakat Tionghoa oleh VOC yang menelan korban 10.000 orang pada 1740. Jumlah korban tersebut terbilang sangat fantastis mengingat populasi warga Tionghoa saat itu berjumlah 15.000 orang. Terjadinya pembantaian tersebut kemudian juga memunculkan reaksi dan gejolak komunitas Tionghoa di luar Batavia yang saat itu tersebar di sepanjang Pulau Jawa, termasuk tindakan-tindakan diskriminasi yang kemudian mengikuti.
Rampungnya Geger Pecinan di Kartasura ditandai dengan hancurnya Kraton Kartasura. Kerusakan yang ditimbulkan dari peperangan mengakibatkan pula perpindahan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta yang berjarak sekitar 11 km jauhnya.

Ia bercerita bahwa setahun setelah pembangunan Kraton Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745, etnis Tionghoa diberi hibahan tanah dari PakubuwanaII untuk membangun tempat ibadah yaitu Klenteng Tien Kok Sie pada tahun 1745. Namun, kraton hanya memfasilitasi tanah dan pembangunan Klenteng dilakukan oleh Tionghoa sendiri.
Selain menjadi klenteng tertua di Solo yang sudah berdiri 300 tahun lebih, ia juga menambahkan bahwa Klenteng ini adalah tempat ibadah tertua di kota tersebut.
Sumantri menyayangkan perlakuan orang sekarang yang berbeda, mudah sekali meng-kafirkan sesuatu apa yang dia lihat dari kaum minoritas. Konotasi kata “Kafir kamu!” sama halnya dengan sebutan yang lebih dahulu muncul, “Cina kamu!”
Saat dihubungi pada Minggu (22/11), Sumantri juga bercerita bahwa saat era Orde Baru di mana banyak peraturan diskriminasi untuk masyarakat etnis Cina dan pemilik agama Tionghoa dirasa lebih sulit dari sekarang. Seperti saat munculnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1974, yang menegaskan bahwa warga Negara Indonesia hanya bisa memilih salah satu dari lima agama (selain Konghucu) yang difasilitasi negara dalam kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu juga mengalami pelarangan beribadah, merayakan hari raya, dan pelarangan mempertunjukan kebudayaan dan kesenian.
“Dulu nggak boleh itu beribadah di klenteng, jadi kami ibadah di rumah diam-diam, banyak yang akhirnya pindah agama. Ibadah saja sulit apalagi merayakan hari raya dan menampilkan kesenian,” kenangnya.
KTP Sumantri juga pernah diberi kode khusus untuk menandai bahwa dirinya bukan pribumi. Di mana pribumi sendiri adalah istilah buatan pemerintah saat itu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang Indonesia ‘asli’. Alhasil, ia juga harus membuat surat kewarganegaraan dan mengganti nama agar tidak bernuansa Tionghoa untuk mempermudah urusan administrasi kependudukan (adminudk).

Yanti (68), yang tidak menyebutkan berapa lama ia sudah berdagang di Pasar Gede juga punya cerita sendiri. Sebagai keturunan Tionghoa di Solo sejatinya ia mengatakan tidak pernah merasakan konflik antarwarga di sana.
“Kalau sekarang ndak ada konflik, warga baik-baik kita sama-sama jualan. Saya memang asli Solo,” jelas Yanti.
Bagi Yanti, selama berdagang di Pasar Gede dan berinteraksi dengan ragam masyarakat berbeda agama di sana, ia tidak pernah melihat masalah yang timbul dari diri masyarakat sendiri. Menurutnya faktor-rektor dari luar lah yang mendorong konflik terjadi.
“Dulu ‘98 ada kerusuhan, ya takut kami (Tionghoa). Tapi sepuluh tahun ini sudah semakin membaik,” ceritanya.
Apa yang dialami oleh Sumantri, Yanti, dan masyarakat Konghucu dan keturunan Tionghoa lain di Indonesia dapat dilihat sebagai proses pemaksaan negara pada masyarakat minoritas. Apalagi diksi pribumi dan non-pribumi yang diciptakan dan masih kerap digunakan hingga sekarang semakin mempertajam situasi kehidupan berharmoni antar-umat beragama dan bermasyarakat di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Deputy Director Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaannya atas pilihan sendiri, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. “Baik melakukan kegiatan ibadah atau ekspresi beribadah di tempat umum atau tertutup,” sambungnya pada Sabtu (7/11).
Pun dalam Hak Beragama dan Berkeyakinan Pasal 18 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik poin 2 dengan bunyi “tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”, harusnya sudah cukup menjadi patokan di Indonesia dalam menentukan regulasi yang melibatkan hak umat beragama.
“Jadi kalau ada upaya pemaksaan justru negara malah melakukan pelanggaran HAM,” tegasnya.
Di Indonesia sendiri pasal-pasal ini juga kemudian diterjemahkan di dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Adapun pasal berikutnya 29 ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang juga menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama.
“Harusnya semua warga negara itu bebas memilih kepercayaan masing-masing dan juga menghargai tentunya,” tambah Sumantri.
Hal-hal yang diceritakan oleh Sumantri pada waktu dulu mulai teredam ketika Presiden B. J. Habibie mengeluarkan dua buah instruksi presiden (Inpres) pada tahun 1999. Pertama, inpres yang menghapuskan istilah pribumi dan nonpribumi, kebudayaan sudah bisa ditampilkan kembali dan memperoleh hak-hak sipil sebagai warga negara.
Inpres Nomor 4 Tahun 1999 yang menghapuskan surat bukti kewarganegaraan RI Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SKBRI). Lalu dilanjutkan dengan penetapan Konghucu sebagai agama pada tahun 2000 dan penetapan Imlek sebagai Hari Libur Nasional pada 2002.
“Meskipun enggak langsung semua hak terpenuhi, tapi pelan-pelan,” ucapnya penuh harap.
Meskipun begitu, Sumantri menceritakan bahwa interaksi antara warga Tionghoa dengan masyarakat lain di Pasar Gede, termasuk keberadaan klenteng sendiri, berjalan dengan harmonis dengan sendirinya. Ia bercerita seperti kesenian Barongsai yang sudah bisa dirasakan tak hanya Etnis Tionghoa, tetapi semua kalangan juga bisa menikmatinya.
“Kini yang jadi Liong (ular naga) dalam Barongsai juga banyak yang bukan Tionghoa. Di sekolah-sekolah juga banyak yang belajar Wushu, Bahasa Mandarin,” tambahnya sambil tersenyum.
Menurutnya hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah sadar akan toleransi yang harus dibangun. Kesenian mampu menjadi salah satu alat untuk mempersatukan umat beragama di Solo.

Nanik (54) selaku pedagang yang sudah lebih 20 tahun berdagang di Pasar Gede juga punya cerita. Selama ia berdagang, ia tidak merasakan adanya konflik terhadap pedagang Tionghoa dan Jawa. Ia menyayangkan apabila terdapat provokator intoleransi khususnya di Surakarta.
“Ya, masing-masing cari rezeki sendiri-sendiri. Sama-sama warga Solo juga,” tutur Nanik saat ditemui langsung.
Nanik menyayangkan jika ada tindakan diskiminasi umat beragama. Maka dari itu, penting bagi Nanik untuk semua orang menghormati dan menghargai orang lain dimulai dari diri sendiri.
“Kalo saya menerapkannya (toleransi – red) dari diri sendiri kemudian lingkungan terdekat. Kita ya ndak bisa memungkiri kalau besok tiba-tiba ada konflik kembali, semoga ya jangan,” harapnya.
Ke depannya Sumantri berharap agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan kaum minoritas yang tersebar di seluruh nusantara. Ia ingin semua dapat merasakan hak-hak sipil seperti yang sudah di rasakan etnis Tionghoa. Karena hidup bertoleransi bukan sekedar teori namun harus juga dapat dipraktikkan langsung.
“Sekarang sudah mulai merasakan hak-hak sipil, hak kebebasan beribadah, dan menikmati kesenian selama sepuluh tahun terakhir ini,” tutupnya.
***
Tulisan ini bagian dari program Workshop Pers Mahasiswa yang digelar oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit (FNF) dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penulis : Lyly Mellya Rahman