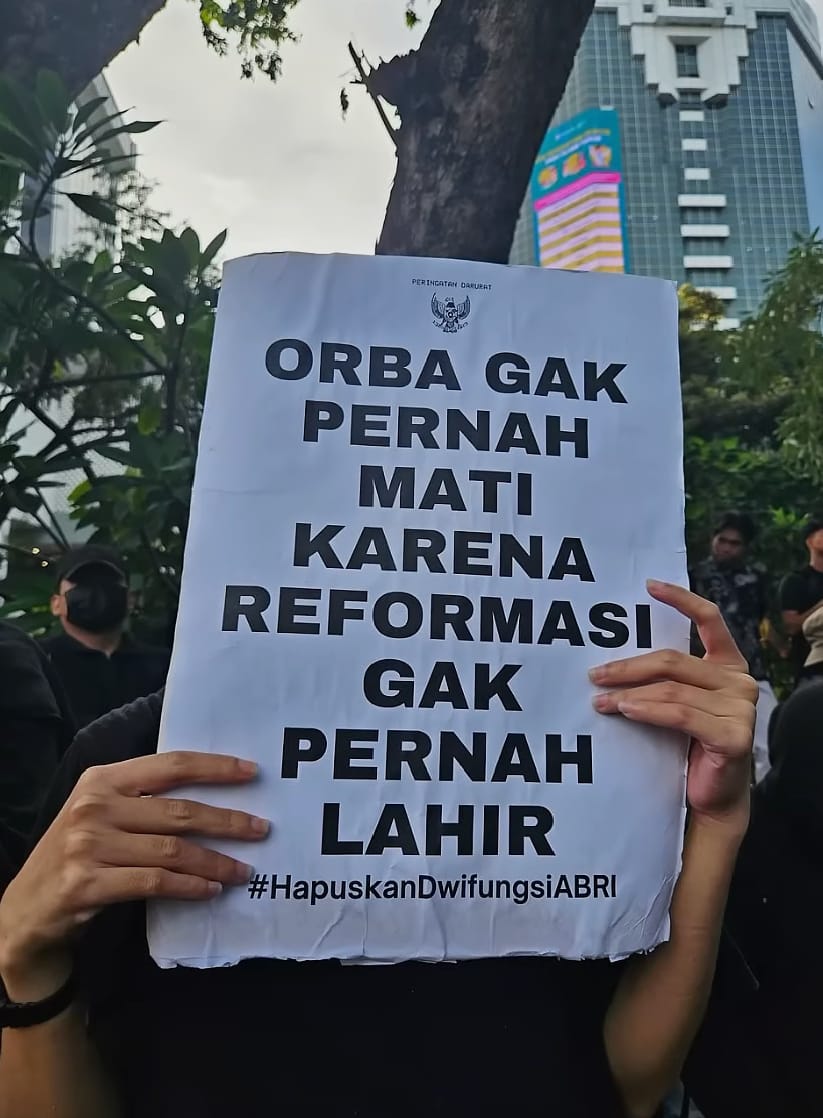Kalau ibu mengatakan bahwa ia tak bisa makan dan karenanya butuh transferan uang, atau bahwa ia mengatakan kesepian dan butuh teman kepada anak-anaknya yang jauh di perantauan. Itu sama sekali bukan sebuah kecengengan. Seorang ibu sesungguhnya bukan tipe perempuan cengeng yang selalu merengek-rengek meminta dikasihani anak-anaknya. Tidak seperti itu. Seorang ibu juga bukan queen drama yang selalu menye-menye setiap kali terjadi mood swing di dalam batinnya.
Seorang ibu amat sekali perkasa dari romantisme-romantisme perilaku seperti itu. Andaikata ibu menampilkan gelagat semacam itu kepada anak-anaknya, ia sendiri pun sebenarnya tak mengerti dan bingung setengah mati: “Mengapa ia melakukannya?”
Dan rupanya, sebagai anak, kita tak cukup mampu bersabar hati untuk membantu supaya ibu mampu menemukan jawabannya. Sebaliknya, banyak dari kita yang justru menjustifikasi perilaku-perilaku ibu semacam itu secara sangat tendensius. Tak sepantasnya itu kita lakukan. Sesungguhnya pun kita menyadari itu, juga menyesalinya, tapi berkali-kali pula kita mengulanginya.
Tak selamanya seorang ibu itu baik. Sebagaimana tak selamanya seorang anak itu baik. Seorang anak berhak kecewa kepada ibu. Begitu pun sebaliknya, seorang ibu berhak kecewa kepada anak. Dengan beratus-ratus alasan kita boleh marah-marah kepada ibu, dan dengan beratus-ratus alasan pula ibu sangat boleh marah kepada kita.
“Aku membenci ibuku. Aku marah kepadanya …” kata seseorang melukiskan perasaannya.
Layu wajahnya menelan kenyataan hidup yang baginya mengerikan. “Aku selalu salah di matanya. Ibu selalu membebani hidupku dengan segala rupa cita-cita dan impiannya tentangku. Kau tahu, itu sangat-sangat menyiksa hatiku. Tak kuat aku dibuatnya.”
Sambil terisak, ia melanjutkan keluh-kesahnya, “Kenapa aku harus dilahirkan dari rahim seorang ibu yang semacam itu?”
Setiap manusia adalah anak dari rahim ibu, dan setiap rahim ibu adalah anak dari zamannya. Suatu zaman yang memiliki corak pikir dan kulturnya sendiri, zaman yang diliputi cara pandangnya masing-masing. Jadi, zaman selalu “mencetak” rahim-rahim ibu. Maka dari itu, setiap zaman sesungguhnya melahirkan ibu zamannya, dan setiap ibu zaman melahirkan anak zamannya—yang berbeda cara pikir, cara bergaul, dan cara membangun pengetahuan.
Kita semua, sebagai anak yang dilahirkan ibu, disadari atau tidak, memang akan menyimpan penyesalan terhadap hidup—yang sedikit banyak selalu menjelma penyesalan terhadap ibu. “Andai saja ibuku adalah …”, “Andai saja ibuku ini seorang …” ,“Andai saja ibuku tidak …” dan seterusnya.
Itulah geliat kekesalan sebagai rupa penyesalan yang menyelimuti kamar batin kehidupan kita, setiap kali kepayahan hidup memukul-mukul dada kita tanpa henti. Tapi, mengapa kita menyesal dan kesal kepada ibu? Salahkah ibu yang melahirkan? Tentu sebagian kita dengan rasa tahu diri mengatakan: “Tidak.”
Memang tidak. Namun ibu bisa menjadi bersalah, tatkala ia tak benar-benar mempersiapkan kelahiran anaknya dengan sedemikian rupa, tapi ibu tetap ingin melahirkan anak. Lalu yang terjadi: anak terlantar, atau anak dibebani harapan setinggi Gunung Everest yang tak semua anak bisa mendaki ke sana. Lebih tak masuk akal lagi, anak dibebani impian tinggi menjulang sampai ke Sidratul Muntaha. Jika itu terjadi, maka ibu bersalah. Sangat bersalah. Ibu telah durhaka kepada anaknya sendiri.
Tapi lain halnya jika ibu sesungguhnya juga korban. Seorang ibu yang tak juga memiliki kebebasan kendali atas hidupnya sendiri. Jangan lupa, seorang ibu juga adalah seorang anak. Seorang anak yang dulu juga terbebani hidupnya. Lalu menjadi ibu. Kemudian melahirkan anak, lalu membebani pula anaknya. Siklus tak berujung. Sebab ibu sendiri tak cukup mampu memutusnya.
Setiap ibu, setiap anak, dan setiap manusia adalah mereka yang tak semuanya mampu untuk dapat melepaskan diri dari jerat tuntutan. Mulai dari tuntutan orang tua yang diguratkan baik dalam catatan pena maupun pengalaman-pengalaman sejarah hidup orang tua. Ingat, dalam kenyataan hidup ini, ada garis melintang yang memberikan pembedaan tegas: bahwa sebagian dari kita itu mewarisi harta, tapi sebagian lagi mewarisi derita (hutang, misalnya).
Tuntutan tak berhenti di situ. Setiap manusia juga dituntut oleh aras kebudayaan yang tidak saja melingkupi, tetapi juga mengatur hidupnya. Dan lagi, adalah pandangan masyarakat, utamanya yang hidup di lingkup sekitarnya, yang menumpahkan tuntutannya melalui sentimen-sentimen nyinyir dan julid. Celakanya, tak semua manusia mampu dan berhasil melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan semacam itu.
Jadi, keluh-kesah yang terlukis dari kata-kata seseorang tadi—yang membenci ibunya, yang marah kepada ibunya, yang teraniaya oleh harapan, cita-cita, dan impian ibunya, yang bertanya mengapa ia dilahirkan dari rahim ibu semacam itu—barangkali adalah keluh-kesah yang juga pernah dilakukan ibunya di masa lampau. Seseorang tersebut, artinya, hanya mengulang saja keluh-kesah ibunya di masa lampau.
Keluh-kesah yang seandainya dibeberkan langsung di hadapan wajah ibunya, bisa jadi langsung membuat ibunya sedih tak terkira. Sebab, sebagai ibu, ia akan merasa gagal menjadi ibu yang baik. Karena ia mengulangi lagi apa yang dulu dilakukan oleh ibunya kepada dirinya, sehingga anaknya mengulangi hal yang sama kepada dirinya sebagaimana ia pernah melakukannya di hadapan ibunya pula. Jadi, bagaimana?
Ibu, dan segala ingatan tentangnya, selalu membawa sukacita yang menderu ke jantung terdalam jiwa hidup dari masing-masing kita.
Betapapun, tak ada gambaran sempurna dalam sosok orang tua, termasuk ibu. Tapi, masing-masing kita, sebagai anak-anak kehidupan yang dilahirkan melalui rahim ibu, adalah saksi hidup dari perjuangan dan pengorbanan seorang ibu—apapun bentuk tindakannya dan bagaimana pun kita kecewa kepadanya. Sebab itu, segala ingatan tentang ibu, akan senantiasa menghadirkan sukacita.
Suka cita itulah, justru, yang membuat kita merasakan hidup dan menjadi dewasa. Sebagaimana kita tak bisa memilih untuk lahir dari rahim ibu yang seperti apa, ibu pun juga tak dapat menentukan untuk melahirkan anak dengan tipikal seperti apa—meskipun sudah ditirakati sedemikian rupa.
Hidup ini (penuh) misteri. Karenanya, ia tampak (sangat) absurd. Keberadaan ibu dalam hidup kita adalah bagian dari misteri tersebut. Sebuah misteri yang hanya akan indah jika kita bersabar untuk terus menikmati kehadirannya, bahkan kalau perlu, kita harus merayakannya tanpa henti di dalam ingatan kesadaran hidup kita ini—sepanjang hayat.
Sedangkan, keberadaan kita dengan segala kekanak-kanakan obsesi, impian, dan belenggu tuntutan-tuntutan yang tidak saja terus menabrak, tapi juga menghimpit kuat kenyataan hidup yang harus kita jalani, adalah representasi dari absurdnya kehidupan ini.
Setuju atau tidaknya, silahkan. Tapi hidup memang harus absurd. Mengapa harus absurd? Karena hidup yang monoton itu membosankan. Apalagi hidup yang terus-menerus monoton. []
Penulis: Ahmad Miftahudin Thohari
Editor: Abril