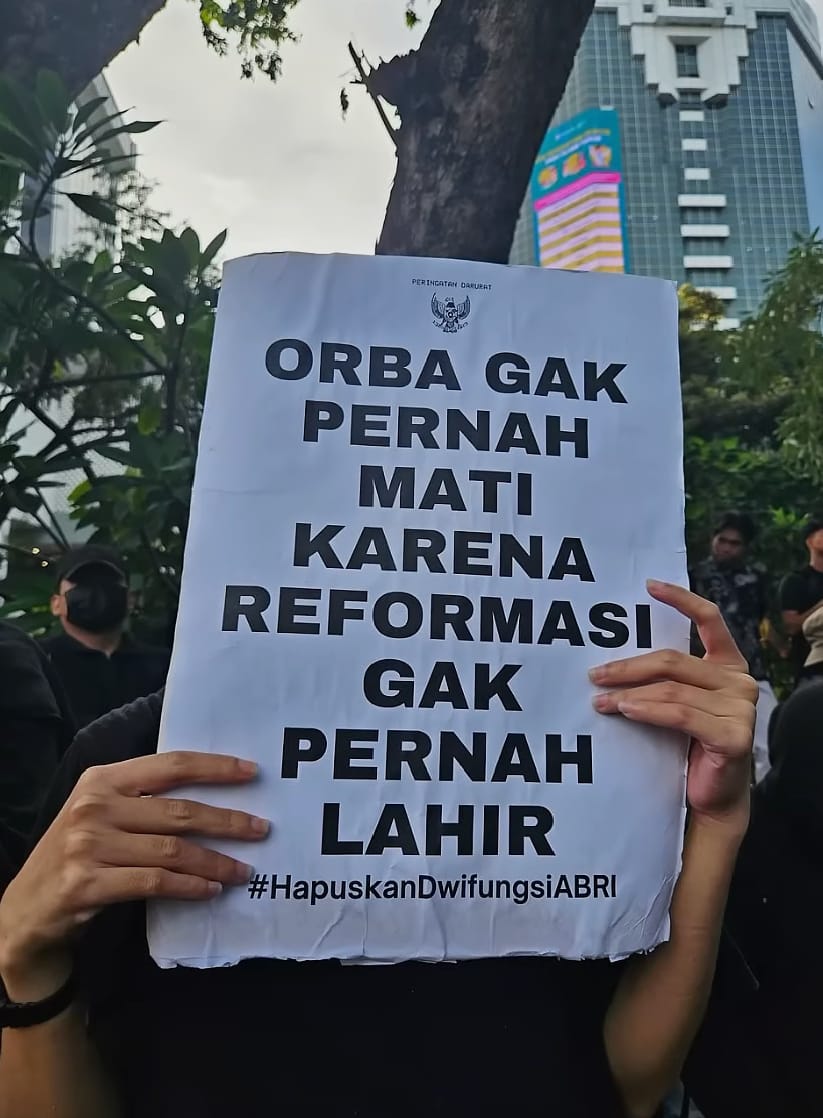Marilah sejenak kita melakukan klangenan, untuk melengangkan dunia kita masing-masing dari hiruk-pikuk persoalan dunia yang semakin hari semakin sumpek ini. Apalagi melihat persoalan-persoalan politik yang berganti-ganti sangat cepat itu. Demi menjaga kewarasan, tetapi sekaligus memahami kegilaan panggung kekuasaan.
Sambil kita menyimak dan mengenang kembali tatkala salah satu punakawan idola kita, Petruk, pernah menjadi Ratu (baca: Raja) yang menciptakan semacam kritik tertentu baik bagi pola kepemimpinan kekuasaan diri dan bangsa kita. Mari, kita duduk dalam keheningan dan perenungan batin masing-masing.
Sebuah Adegan: Petruk Dadi Ratu
Suatu ketika, Petruk Kantong Bolong mengenang tentang bagaimana dirinya dulu bisa sampai menjadi seorang “Raja”—seorang pemimpin.
Kala itu, sang Bendoro, yakni Raden Abimanyu sedang menderita sakit. Abimanyu inilah seorang perantara yang nantinya akan mewariskan kursi (tahta) Palasara—pendiri Astina—kepada Parikesit, anaknya sendiri. Bersamaan dengan sakitnya itu, pergilah ketiga wahyu yang dimilikinya. Yakni, wahyu maningkrat, yang menyebarkan benih keratuan. Wahyu cakraningrat, yang menjaga keberadaan dirinya sebagai ratu. Dan, wahyu widayat, yang melestarikan hidupnya juga sebagai seorang ratu.
Pada saat yang sama, tiba-tiba ketiga wahyu tersebut menghinggapi tubuh Petruk. Bahkan, termasuk Jamus Kalimasada sebagai tonggak utama mutu kewibawaan dan keampuhan raja-raja keraton juga hinggap dalam diri Petruk.
Singkat cerita, lantaran Jamus Kalimasada sudah merasuki tubuhnya, membuat Petruk menjadi sosok yang pilih tanding untuk menjatuhkan raja-raja yang ada. Sampai akhirnya, ia berhasil menobatkan dirinya sebagai Prabu Belgeduwelbeh Tongtongsot.
Pada saat dirinya sudah kehilangan dirinya sebagai seorang diri—Petruk lantas melabrak semua aturan hukum serta tatanan-tananan sistem “mainstream” yang sudah berlaku lama sebagai model pelaksanaan kekuasaan di Bumi Marcapada. Maka, seluruh anggapan umum ia jungkir balikkan dan putar balikkan bahwa pemimpin boleh bertindak seenak wudele dewe, bahwa boleh secara gembelengan ketika sedang nyunggi wakul, dan tidak akan ada hukuman serta tidak akan ada somasi maupun interupsi yang boleh dilakukan oleh siapa pun ketika umpamanya segone tumpah dadi sak latar, berserak-serakan. Bahwa raja itu bebas nilai untuk berlaku adil atau tidak terhadap seluruh hidup rakyatnya. Serta banyak lagi hal-hal di luar nalar sehat yang dilakukan oleh Ki Petruk Kantong Bolong itu.
Kelakuan Prabu Kantong Bolong semakin hari semakin sama sekali membuat resah seluruh raja-raja lain. Bahkan, Kahyangan Jonggring Saloka tak tertinggal juga ikut-ikutan gelisah karenanya. Kawah Candradimuka pun tiba-tiba mendidih dan meletup-letup, ini pertanda adanya “ontran-ontran” yang akan membahayakan kekuasan para dewa.
Supaya tak semakin terjadi chaos berkepanjangan, dilakukanlah perundingan. Lalu, secara aklamasi telah disepakati akan dilakukan semacam pelaksanaan skenario guna “mengeliminir” raja-raja yang menjadi biang keladi keresahan publik. Dengan demikian, dibentuklah persekutuan antara raja dan dewa yang tujuannya adalah untuk melenyapkan “suara-suara sumbang” pengganggu tatanan kenyamanan yang telah lebih dulu dibentuk dan dijalankan selama ini. Akan tetapi, ternyata rencana itu gagal total. Bukannya Prabu Kantong Bolong lenyap, justru ia semakin moncer. Ia malah mengamuk sejadi-sejadinya. Siapa saja yang berani mendekatinya akan dihajar habis-habisan, dirampungi uripe.
Prabu Kresna dan Baladewa saja berhasil dibuat babak belur. Sang penguasa kahyangan Batara Guru pun lari terbiri-birit. Semua aji kesaktian milik para raja dan dewa seperti tidak berarti sama sekali di hadapan Sang Prabu Kantong Bolong. Bahkan, tahta Jonggring Saloka juga berhasil dikuasai oleh raja dadakan ini. Keadaan semakin semrawut tak karuan.
**
Ketika Petruk menjadi raja di negara yang dinamainya Lojitengara. Dan ia menggelari dirinya Prabu Belgeduwelbeh. Ternyata untuk bisa kukuh menjadi raja, ia membutuhkan dampar (kursi) kerajaan Astina, warisan Palasara.
Petruk memerintahkan dua patihnya, “Hei, Bayutinaya (titisan Anoman) dan Wisandhanu (titisan Wisanggeni, anak Arjuna), ambilkan tahta Palasara di kerajaan Astina untukku!”
Kedua utusan itu pun berhasil membawakan dampar (tahta) tersebut. Prabu Belgeduwelbeh akhirnya mencoba mendudukinya. Begitu dilakukan, ia malah terjungkal. Diulangi mendudukinya beberapa kali dan beberapa kali pula ia terjungkal. Akhirnya, Sang Prabu menyerah.
Namun, tiba-tiba, Sang Prabu dibisiki oleh penasihat kerajaan. “Mohon maaf, Gusti Prabu. Begini, agar Baginda tak terjungkal. Baginda harus memperoleh terlebih dahulu boneka yang bisa dililing (bisa dilihat dan ditimang).”
Tanpa pikir panjang, langsung Sang Prabu menyuruh kedua utusannya, Bayutinaya dan Wisandhanu, untuk mencari boneka yang dimaksud itu. Tanpa perlawanan dan kesulitan berarti, kedua utusan tersebut berhasil mendapatkan boneka tersebut—tak lain ternyata adalah tubuh Abimanyu yang sedang sakit—dan membawakannya ke Sang Prabu. So, Sang Prabu mendudukan boneka itu kepangkuannya sendiri. Tanpa diduga, Raden Abimanyu seketika sembuh dan berkata, “kau mustahil bisa menduduki tahta itu (dampar Astina) jika kau tidak memangku diriku.”
Tiba-tiba saja guncangan dahsyat terjadi, seketika itu juga. Kahyangan berguncang dan Bumi Marcapada bergolak. Sang Prabu Belgeduwelbeh terlihat hendak menampilkan pertunjukan dahsyatnya. Tak ada yang berani mendekatinya—apalagi melawannya. Semua bulu kuduk berdiri sedemikian rupa karenanya. Situasi dan kondisi tampak semakin membuncah. Seluruh gunung akan meletus jika ini dibiarkan begitu saja.
Sampai akhirnya, datanglah Kiai Semar Bodronoyo—Sang Batara Ismaya—sekaligus Ki Lurah Karang Kadempel turun tangan mengendalikan situasi.
“Ngger, Petruk anakku!” Semar berujar pelan begitu lembut, suaranya serak dan berat seperti biasanya, “jangan kau kira aku tidak mengenalimu wujudmu, Ngger!”
Kiai Semar melanjutkan, “apa yang sudah kau lakukan, Thole? Apa yang kau inginkan, He? Apa kau sudah merasa hina menjadi seorang kawula alit? Apa kau merasa begitu lebih mulia bila telah menjadi raja?” Sorot matanya menatap tajam bola mata Petruk, tetapi menusuk lembut, “sudahlah, Ngger. Jadilah dirimu sendiri.”
Seketika, Prabu Kantong Bolong yang gagah perkasa dan tampan itu layu seperti kehilangan tulang belulangnya. Ia langsung berubah menjadi Petruk kembali.
Petruk Insaf
Petruk selalu tersenyum-senyum sendiri setiap kali mengingat peristiwa dirinya sendiri kala ia jadi Ratu.
“Pada saat itu, saya mengalami dan sadar bahwa saya ini hanyalah kawula alit. Bagaimanapun, saya akan tetap tinggal sebagai kawula alit. Tak mungkinlah saya bisa duduk sebagai seorang raja. Saya ini hanya rakyat kecil, tugas saya hanyalah memangku raja supaya ia dapat tenang menduduki dampar(tahta)nya.” Petruk mulai merenung.
“Bendoroku, Raden Abimanyu itu hanya dapat duduk di atas tahta kerajaan karena saya bersedia memangkunya. Jadi, raja tidak akan bisa menjadi raja kalau ia tidak dipangku oleh kawula-kawula alit, seperti saya ini.” Ia melanjutkan renungannya, sambil memandang hamparan tanah datar di hadapannya.
Dulu, Ki Petruk tidak paham, mengapa ketiga wahyu itu pergi meninggalkan tuannya. Dan malah menghinggapinya. Sekarang ia paham bahwa wahyu itu sebenarnya hanya pergi untuk sementara saja. Perginya hanya sebatas nitik. Menengok siapa gerangan yang dapat memangku orang yang kedunungan (dihinggapi) wahyu. Dan wahyu tidak bisa asal hinggap. Dia akan hinggap pada orang yang layak dihinggapi—dan orang tersebut harus dipangku, misalnya, oleh Petruk, sang rakyat atau sang kawula alit. “Benarlah,” katanya dalam hati. “Pemimpin sejati itu tidak dicetak—tidak bisa direkayasa—, tetapi dilahirkan.”
Masih di tempat yang sama dan pada posisi yang sama di hadapan tanah datar itu. Pikiran Kiai Kantong Bolong melayang sedih tatkala mengingat gugurnya sang tuan Abimanyu dalam Perang Bharatayudha. Saat itu, Petruklah yang menggendong dan ngurusi jenazah Abimanyu. Dan Petruk pula yang membakar mayat Abimanyu menuju alam mokshya. “Betapa pun hinanya saya sebagai rakyat, tetapi sayalah yang berandil besar menghantarkan jenazah Sang Raja menuju alam kesempurnaannya. Sampai mokhsya-nya pun. Hanya rakyatlah yang dapat menyempurnakan hidup seorang raja, bahkan ketika ia berhadapan dengan akhiratnya sekalipun,” ujar Petruk.
Rakyat, sang kawula akan ada sepanjang zaman. Sementara raja itu tidak abadi. Ia bertahta hanya dalam kurun waktu tertentu. Bahkan sudah diatur jelas masa periodenya, sebagaimana pekerja outsourching. Maka, ketika masa itu telah lewat, ia harus turun atau ‘binasa’.
“Rakyat memang akan terus selalu ada. Buktinya, saya ini ada di sepanjang zaman,” kata Petruk. “Menjadi punakawan, hamba menemani penguasa-penguasa zaman dari masa ke masa, sampai hari ini. Kawula iku ana tanpa wates, nanging ratu iku anane namung winates.”
Di tengah perenungannya, tiba-tiba bibir Petruk bergerak nyerocos tanpa disadarinya sendiri. “Sebenarnya, hanyalah rakyat yang dapat membantu pengusasa menuliskan sejarahnya.” Petruk lantas berdiri tegak, sorot matanya tajam seperti Elang hendak menyonsong mangsanya. “Maka, seharusnya penguasa itu menghargai kawulanya, rakyatnya, para abdi-abdinya. Bukannya malah ngrayah uripe kawula. Tak tahu diri betul! Kuasa iku kudu ono lelabuhane. Kuasa itu hanya sarana untuk bahan lelabuhan. Raja itu bukan raja lagi, kalau sudah ditinggal rakyatnya. Jadi, siapa yang lebih penting dan tinggi kedudukannya, raja atau rakyat? Siapa yang akan memangku raja agar ia duduk tenang, kalau bukan rakyat? Raja yang tidak dipangku rakyat adalah raja yang koncatan wahyu,” tutur Petruk sambil menghela napas.
“Tapi, Ki Petruk, kenapa banyak penguasa yang tak memperhatikan rakyatnya, yang malah menginjak dan menghina kawulanya sendiri. Toh, meskipun begitu, ia tetap mampu duduk di atas tahtanya?” Suara Bagong yang dipolos-poloskan terdengar dari semak-semak belukar belakang rumah.
“Dalam pewayangan pun, ada juga penguasa yang tak dipangku oleh rakyat seperti saya ini, Gong,” jawab Petruk. “Dia adalah Dasamuka yang lalim. Dia adalah Duryudana yang serakah. Nah, seperti halnya hanya ada satu tahta Palasara, demikian pula hanya ada satu tahta rakyat. Duryudana memang berkuasa, tetapi tak pernah sekalipun berhasil menduduki tahta Palasara. Dan banyak penguasa-penguasa—di bumi bagian mana pun dan di zaman macam apa pun itu—yang berkuasa, tapi mereka sama sekali tak bertahta di dampar yang sebenarnya yakni tahta rakyat ini,” pungkas Petruk dengan menunjuk hatinya sendiri.
Bagong lantas keluar, dan malah bertepuk tangan.
“Kenapa bertepuk tangan, Gong?”
“Loh, omongan Kakang Petruk itu harus diapresiasi. Dan siapa lagi yang mau mengapresiasi kalau bukan Mas Bagong ini, Truk? Memangnya, omonganmu itu didengar oleh orang, selain Bagong ini, He? Itu loh, hidungmu itu terlalu offside, jadinya belum sampai keluar kata-katamu sudah langsung disemprit oleh banyak orang,” jawab Bagong terkekeh-kekeh.
“Woo, dasar gudel! Lucknut!”
“Bangkeee! Prabu Belgedu!”
Bagong semakin terbahak-bahak sambil berlalu pergi.
Tiba-tiba, setelah jejak Bagong hilang tanpa bekas. Tanah datar di hadapannya itu bersenandung dibarengi gemerisik dedaunan di sekitarnya. Makin lama semakin keras pula lantunannya, bahkan kini berubah juga menjadi Senandung Panitisastra: “Dulu tanah itu adalah hutan lebat yang bersinga. Singa bilang, kalau hutan tak kujaga tentu ia akan dibabat habis manusia. Hutan bilang, kalau singa tak kunaungi dan pergi dariku, pasti ia akan ditangkap manusia. Akhirnya singa dan hutan sama-sama binasa. Singa yang tak mau berhutan dibunuh manusia, hutan yang tak berkenan bersinga dibabat habis manusia …”
“Raja dan rakyat harus wengku-winengku, rangkul-merangkul, seperti singa dan hutan, seperti Abimanyu dan Petruk.” Ujar Petruk seraya menyambung senandung tembang Panitisastra itu. []
Penulis: Ahmad Miftahudin Thohari
Editor: Izza